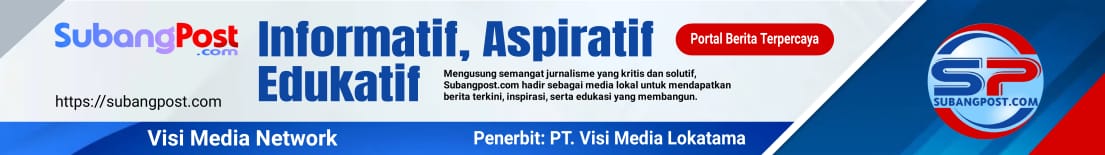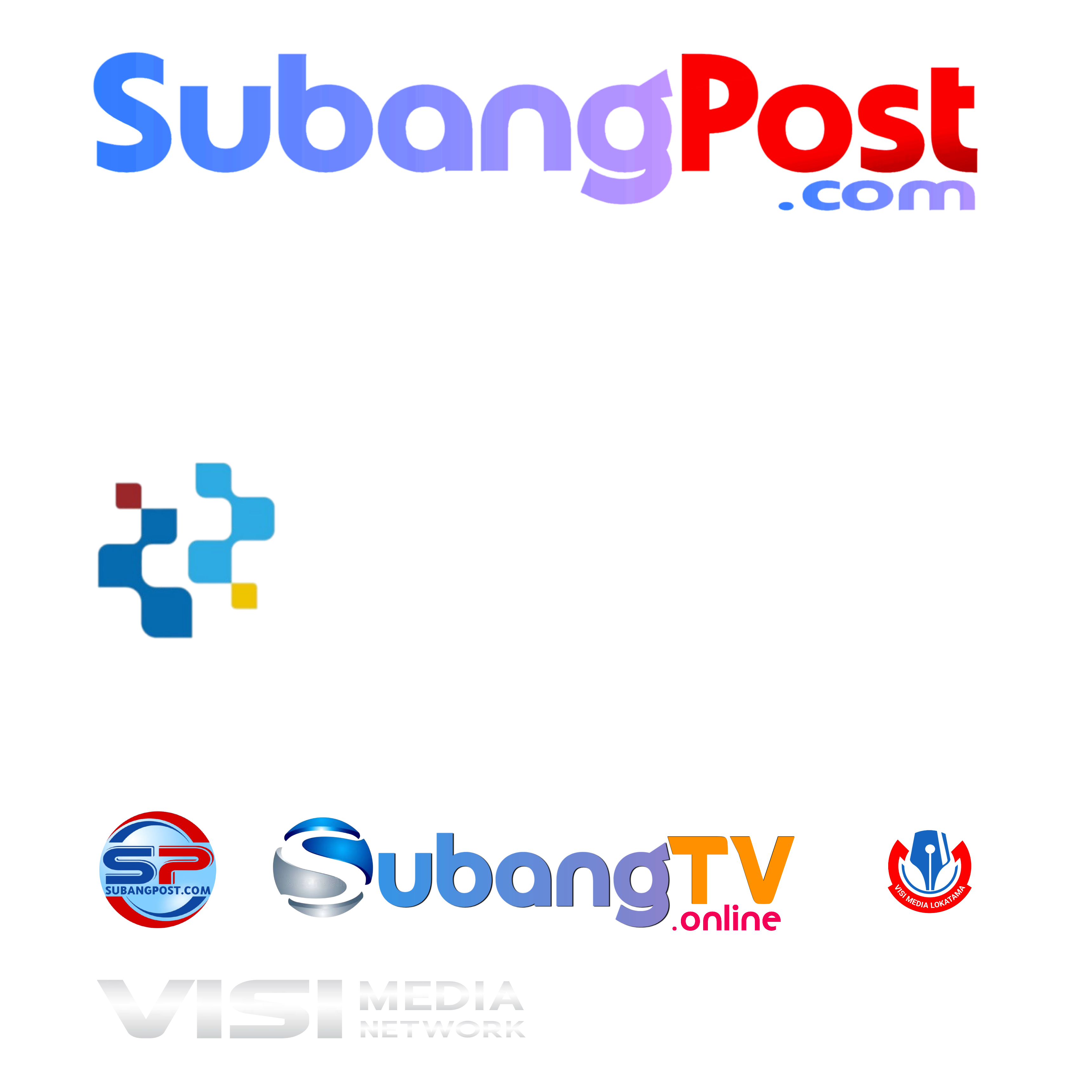Swasembada pangan tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan reforma agraria, sebab keduanya membentuk fondasi struktural bagi pembangunan pertanian yang adil, produktif, dan berkelanjutan.
Oleh: Sacim Zein
Wacana swasembada pangan di Indonesia selalu mengemuka dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya. Namun, pembahasan yang muncul sering kali terfokus pada indikator teknis seperti volume produksi, luas panen, dan ketersediaan pupuk. Orientasi kuantitatif ini menyederhanakan persoalan pangan yang jauh lebih kompleks.
Amartya Sen dalam Poverty and Famines menegaskan bahwa kelaparan tidak semata diakibatkan oleh kekurangan produksi, tetapi lebih berkaitan dengan akses, distribusi, dan struktur penguasaan sumber daya. Dengan demikian, swasembada pangan tidak dapat dilepaskan dari persoalan agraria yang menjadi fondasi sektor pertanian.
Data produksi pangan Indonesia menunjukkan capaian yang relatif stabil. Pada 2024, BPS mencatat produksi padi sebesar 53,14 juta ton GKG, setara dengan 30,62 juta ton beras. Pada Mei 2025, produksi mencapai 4,98 juta ton GKG atau 2,87 juta ton beras. Secara makro, angka ini menunjukkan kemampuan produksi yang memadai. Namun, di balik keberhasilan tersebut, terdapat persoalan struktural yang mengancam keberlanjutan produksi.
Lahan baku sawah yang menjadi basis utama produksi padi terus mengalami penyusutan. Indonesia saat ini memiliki sekitar 7,46 juta hektare lahan sawah, tetapi angkanya terus menurun dengan kehilangan 79.967 hektare dalam beberapa tahun terakhir. Tingkat konversi sawah menjadi kawasan non-pertanian diperkirakan mendekati 1% per tahun, terutama di wilayah yang mengalami percepatan urbanisasi.
Fenomena penyusutan lahan dan fragmentasi kepemilikan menyebabkan skala usaha tani semakin kecil. Mayoritas petani Indonesia kini menggarap lahan kurang dari 0,5 hektare, kondisi yang telah dibahas Clifford Geertz melalui konsep agriculture involution: peningkatan jumlah tenaga kerja pertanian tanpa perluasan lahan mengakibatkan stagnasi produktivitas.
Di tengah struktur yang demikian sempit, swasembada pangan lebih bertumpu pada intensifikasi teknis ketimbang reformasi struktural. Persoalan ini semakin diperburuk oleh kecenderungan konsentrasi penguasaan tanah. Karl Kautsky dalam The Agrarian Question menjelaskan bahwa kapitalisme cenderung mengonsentrasikan tanah kepada pemilik modal besar.
Di Indonesia, konsesi HGU berskala besar, proyek food estate, dan perluasan perkebunan menguatkan pola tersebut. Akibatnya, petani kecil semakin terpinggirkan. Analisis Henry Bernstein turut memperjelas bahwa sistem pangan berada dalam relasi kekuasaan: kontrol atas benih, pupuk, harga gabah, dan distribusi pangan didominasi segelintir aktor ekonomi, sehingga petani tetap menjadi pihak paling rentan dalam rantai nilai pangan.
Dalam konteks inilah reforma agraria menjadi instrumen yang esensial. Menurut Gunawan Wiradi, reforma agraria bukan hanya program sertifikasi lahan, tetapi penataan ulang struktur penguasaan tanah untuk menciptakan keadilan agraria.
Banyak negara membuktikan bahwa redistribusi tanah merupakan fondasi bagi peningkatan produksi pangan. Jepang dan Korea Selatan adalah contoh klasik di mana reforma agraria menjadi prasyarat industrialisasi sekaligus swasembada pangan.
Kajian Michael Lipton mengenai small farmers are efficient menunjukkan bahwa petani kecil memiliki tingkat efisiensi yang tinggi ketika mereka memperoleh kepastian hak atas tanah; kepastian ini mendorong investasi jangka panjang dalam teknologi, perbaikan irigasi, dan praktik budidaya berkelanjutan.
Keterkaitan antara reforma agraria dan swasembada pangan dapat dijelaskan melalui beberapa dimensi. Pertama, reforma agraria meningkatkan pemerataan akses lahan sehingga petani penggarap memperoleh sumber daya produksi utama secara lebih adil. Kedua, kepastian hak atas tanah mendorong peningkatan produktivitas melalui intensifikasi yang dilakukan secara mandiri oleh petani. Ketiga, peningkatan hasil panen berkontribusi pada kesejahteraan petani, yang merupakan elemen penting dalam ketahanan pangan nasional. Keempat, distribusi lahan terlantar kepada kelompok tani dapat mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang sebelumnya tidak produktif. Kelima, reforma agraria memperkuat fondasi ketahanan pangan berkelanjutan dengan mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkokoh kedaulatan pangan dari tingkat lokal hingga nasional.
Dengan demikian, swasembada pangan tidak dapat dipahami hanya sebagai pencapaian angka surplus produksi. Swasembada yang tidak dibangun di atas struktur agraria yang adil akan rapuh karena berdiri di atas lahan yang menyusut, petani yang terpinggirkan, dan ketimpangan penguasaan sumber daya. Sebaliknya, reforma agraria yang tidak diintegrasikan dengan sistem produksi pangan nasional hanya menghasilkan petani yang memiliki tanah tetapi tidak berdaya dalam pasar pangan yang terintegrasi.
Swasembada pangan dan reforma agraria merupakan dua aspek dari satu proyek besar: membangun sistem pangan nasional yang berdaulat, berkelanjutan, dan berbasis keadilan. Tanpa pembaruan struktur agraria, swasembada hanya menjadi capaian administratif; tanpa kedaulatan pangan, reforma agraria kehilangan relevansinya dalam konteks pembangunan nasional. Kedua agenda ini harus diposisikan sebagai fondasi simultan yang menentukan masa depan pangan Indonesia.
* Penulis adalah seorang Jurnalis dan pendiri subangpost.com